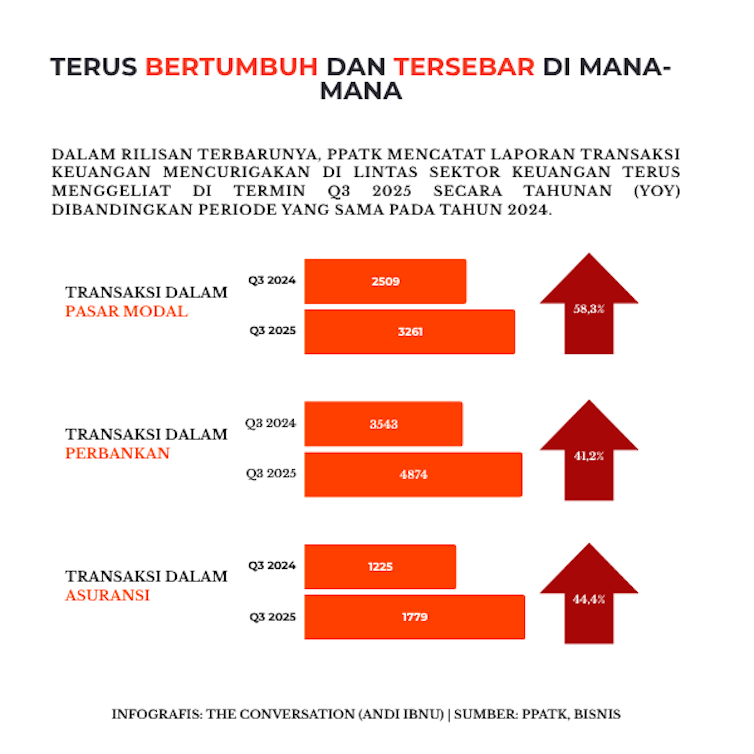20 tahun perdamaian GAM-pemerintah: Pelaku kejahatan perang di Aceh masih dibiarkan
- Written by Darul Mahdi, PhD Candidate at UQ School of Law, The University of Queensland

● Sudah dua dekade sejak Perjanjian Helsinki diteken, kejahatan perang oleh militer Indonesia masih belum diadili.
● Hukum di Indonesia belum mengatur kejahatan perang, sehingga konflik bersenjata sulit ditindak.
● Pemerintah harus jujur menghadapi masa lalu dan memastikan pelanggaran serupa tidak akan terulang lagi.
Pada 15 Agustus 2005, tepat 20 tahun lalu, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani kesepakatan perdamaian di Finlandia, yang dikenal dengan Perjanjian Helsinki[1].
Kesepakatan ini mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir 30 tahun di Aceh.
Perjanjian bersejarah tersebut dicapai beberapa bulan setelah tsunami dahsyat pada 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari 227 ribu orang, termasuk sekitar 167 ribu penduduk Aceh[2].
Perdamaian antara pemerintah dan kelompok GAM kala itu merupakan pencapaian luar biasa. Langkah ini memungkinkan Aceh membangun kembali dan menstabilkan wilayah yang selama bertahun-tahun dilanda kekerasan.
Sayangnya, perdamaian ini masih menyisakan sejumlah pelanggaran berat dan dugaan kejahatan perang oleh militer Indonesia selama 1976 - 2005 yang hingga kini belum tersentuh pengadilan.
Apa yang terjadi?
Pemberontakan bersenjata meletus di Aceh pada 1976. GAM sebagai inisiatornya, menuntut kemerdekaan dari apa yang mereka anggap sebagai kendali “neokolonial”[3] Indonesia.
Gerakan tersebut mendapat dukungan yang luas dari berbagai komunitas lokal yang kecewa dengan pemerintah Indonesia atas marjinalisasi politik dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kekecewaan atas ketidakadilan pembagian hasil sumber daya kian menguat setelah penemuan gas alam di Aceh Utara[5] pada 1971.
Ketegangan meningkat drastis saat Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer[6] (DOM) dari 1989 hingga 1998.
Read more: Mengapa pendidikan di Aceh perlu mengajarkan soal kesepakatan damai dan rekonsiliasi[7]
Upaya perdamaian beberapa kali digagas[8] sejumlah pihak, tetapi berbuah kegagalan. Puncaknya, situasi memburuk ketika pemerintah memberlakukan Darurat Militer[9] pada 2003. Upaya ini menjadi pengerahan militer terbesar sejak Indonesia menginvasi Timor Timur[10] pada 1975.
Konflik tersebut berakhir adanya Kesepakatan Helsinki, setelah melalui lima tahap perundingan. Beberapa isi kesepakatan tersebut di antaranya adalah memberikan amnesti terhadap simpatisan GAM, penghentian aksi kekerasan dari semua pihak, hingga pembentukan Pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Sudah diakui, tapi tak diadili
Pada 11 Januari 2023, Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai presiden mengakui 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM)[11] berat masa lalu di Indonesia.
Ia bahkan berjanji pemerintah bakal memulihkan hak-hak korban dan mencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang.
Tiga dari pelanggaran HAM berat tersebut terjadi di Aceh saat operasi militer pemerintah melawan GAM. Salah satunya adalah Tragedi Simpang KKA[12] pada 3 Mei 1999. Saat itu tentara menembaki kerumunan warga sipil di dekat pabrik Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara.
Read more: Aceh bangkit berkat partisipasi aktif masyarakat dan badan usaha desa[13]
Insiden tersebut terjadi menyusul penggeledahan dan intimidasi militer selama berhari-hari di daerah tersebut setelah seorang tentara dilaporkan hilang[14].
Ketika penduduk desa berkumpul dan seorang pemimpin setempat mencoba meredakan situasi, beberapa truk militer tiba. Sekitar tengah hari, setelah serangkaian provokasi, pasukan menembaki warga sipil tak bersenjata saat mereka berusaha melarikan diri.
Menurut Komnas HAM, setidaknya 23 warga sipil tewas[15] akibat tembakan oleh personel militer dalam insiden tersebut.
Padahal hukum internasional[16] tegas menyebutkan penyerangan warga sipil dengan sengaja di tengah konflik bersenjata sebagai kejahatan perang. Dalam kasus yang lebih berat, penyerangan bisa masuk ke kategori kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.
Bukti-bukti menunjukkan dengan jelas bahwa peristiwa tersebut memenuhi kriteria konflik bersenjata internal[18] sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949[19]—dengan GAM sebagai kelompok bersenjata terorganisir[20] dan tingkat kekerasan yang tinggi.
Kekosongan hukum melanggengkan impunitas
Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia melakukan sejumlah reformasi hukum. Salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM[21], yang mengadopsi sebagian besar rumusan dari Statuta Roma 1998[22].
Namun, undang-undang ini hanya mengatur dua kejahatan internasional: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang sama sekali tidak diatur, berbeda dengan ketentuan dalam Statuta Roma.
Read more: Ternyata, bahasa punya peran dalam pengurangan risiko konflik[23]
Kekosongan ini juga tak kunjung diisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[24] yang baru disahkan pada 2023.
Artinya, melakukan tindakan kejahatan dalam konflik bersenjata dianggap “dapat diterima[25]”, selama tidak melampaui ambang batas sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.
Ketiadaan aturan hukum ini membuat tindakan yang seharusnya tergolong kejahatan perang di Indonesia, termasuk saat konflik GAM-pemerintah, tidak bisa diproses.
Di negara dengan sejarah panjang konflik bersenjata internal–dari Aceh hingga Timor Timur, hingga kekerasan bersenjata yang masih berlangsung di Papua, kekosongan ini melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga sipilnya di situasi konflik.
Perlu mengakui dosa masa lalu
Pemerintah perlu segera menjamin akuntabilitas dan menjamin tegaknya keadilan bagi para korban konflik di Aceh.
Pertanggungjawaban bukan soal membuka kembali luka lama, melainkan tentang menghadapi masa lalu dengan jujur. Negara pun perlu memastikan pelanggaran serupa tidak akan terulang di masa depan.
Indonesia perlu melakukan sejumlah langkah-langkah segera berupa:
Memasukkan kejahatan perang ke hukum nasional, agar hukum Indonesia selaras dengan hukum internasional dan menutup celah impunitas yang masih ada.
Menjamin akses terhadap keadilan, reparasi dan rehabilitasi bagi para korban dan keluarga mereka, baik melalui jalur peradilan maupun mekanisme nonyudisial.
Dua dekade terakhir perdamaian di Aceh merupakan pencapaian besar. Namun, perdamaian tanpa keadilan akan terasa rapuh, meninggalkan luka yang masih terus menganga.
References
- ^ Perjanjian Helsinki (ppid.acehprov.go.id)
- ^ 167 ribu penduduk Aceh (link.springer.com)
- ^ kendali “neokolonial” (library.fes.de)
- ^ Ariful Azmi Usman/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ penemuan gas alam di Aceh Utara (www.ictj.org)
- ^ Daerah Operasi Militer (kkr.acehprov.go.id)
- ^ Mengapa pendidikan di Aceh perlu mengajarkan soal kesepakatan damai dan rekonsiliasi (theconversation.com)
- ^ Upaya perdamaian beberapa kali digagas (www.jstor.org)
- ^ Darurat Militer (aceh.tribunnews.com)
- ^ menginvasi Timor Timur (www.jstor.org)
- ^ mengakui 12 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (nasional.kompas.com)
- ^ Tragedi Simpang KKA (aceh.tribunnews.com)
- ^ Aceh bangkit berkat partisipasi aktif masyarakat dan badan usaha desa (theconversation.com)
- ^ seorang tentara dilaporkan hilang (www.amnesty.nl)
- ^ 23 warga sipil tewas (www.komnasham.go.id)
- ^ hukum internasional (www.icc-cpi.int)
- ^ Zulhidayat AY/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ konflik bersenjata internal (www.icc-cpi.int)
- ^ Konvensi Jenewa 1949 (ihl-databases.icrc.org)
- ^ GAM sebagai kelompok bersenjata terorganisir (scholarspace.manoa.hawaii.edu)
- ^ Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (peraturan.bpk.go.id)
- ^ Statuta Roma 1998 (www.icc-cpi.int)
- ^ Ternyata, bahasa punya peran dalam pengurangan risiko konflik (theconversation.com)
- ^ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (peraturan.bpk.go.id)
- ^ dapat diterima (www.cambridge.org)
- ^ Zulhidayat AY/Shutterstock (www.shutterstock.com)
Authors: Darul Mahdi, PhD Candidate at UQ School of Law, The University of Queensland