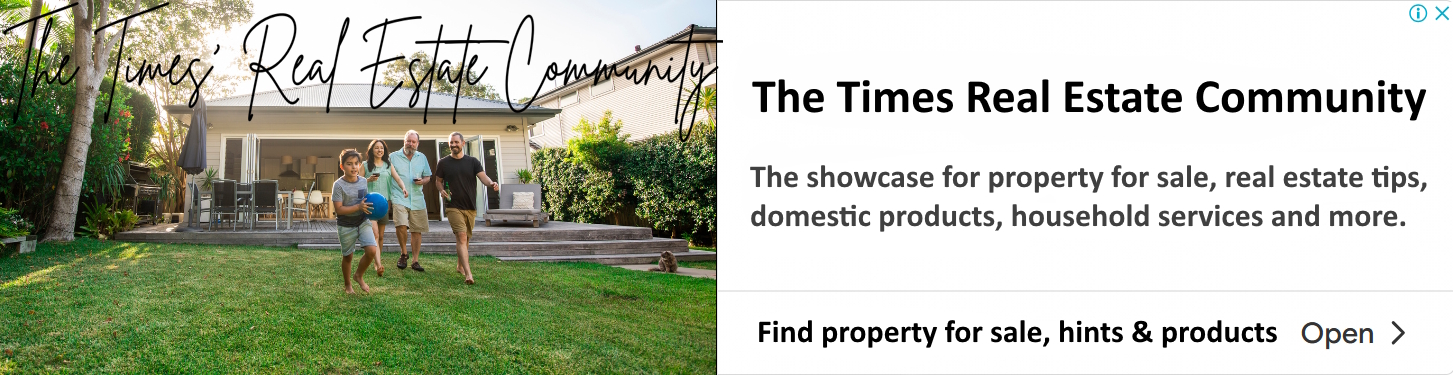Zodiak, MBTI, dan tarot: Mengapa sebagian kaum muda percaya pseudosains
- Written by Muhammad Naufal Waliyuddin, Researcher of Youth and Religious Studies. Doctoral candidate in Islamic studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
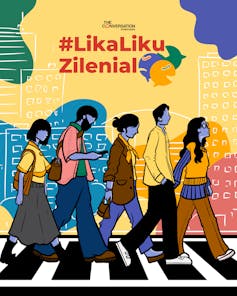
● Banyak kaum muda yang percaya zodiak dan bentuk-bentuk pseudosains lainnya.
● Meski tak ilmiah, pseudosains menawarkan narasi personal yang nyaman dan mudah dipahami.
● Jika tidak diimbangi dengan pemikiran kritis, kepercayaan pada pseudosains bisa berdampak serius.
Olivia (27 tahun) sudah lama akrab dengan dunia zodiak. Ia bahkan menggunakan aplikasi khusus astrologi bernama Co-star yang mengklaim memadukan data NASA (National Aeronautics and Space Administration) dan tafsir bintang-bintang. Aplikasi ini menyediakan fitur personalisasi dan jasa ramal melalui layanan ramalan berbayar.
Bagi Olivia, hal tersebut penting diketahui karena rasi bintang ketika ia lahir mungkin menyimpan petunjuk tentang jalan hidupnya.
Olivia adalah satu dari 3 kaum muda yang saya wawancarai untuk mengetahui mengapa kaum muda percaya—dan tidak percaya—pada pseudosains, serta apa dampak yang mengikutinya.
Popularitas yang melampaui zaman
Seperti yang diyakini Olivia, zodiak memang mengklaim[1] bahwa ada hubungan antara benda-benda angkasa dengan peristiwa di bumi—khususnya kepribadian, nasib, dan urusan umat manusia. Kepercayaan semacam ini sudah ada sejak era Babilonia dan berkembang menjadi 12 simbol zodiak dalam kebudayaan Yunani Klasik[2].
Klaim, kepercayaan, atau praktik yang tampak ilmiah namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya ini terbukti tak lekang dimakan zaman.
Buktinya, lebih dari 80% orang dewasa di seluruh dunia tahu zodiak mereka[3]. Bahkan, industri di bidang ini memiliki nilai bisnis miliaran dolar[4] karena telah merambah platform digital hingga aplikasi berbayar.
Hal yang sama juga terjadi pada tren membaca tarot, garis tangan[5], hingga MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)[6] yang sudah banyak dikritik[7] oleh komunitas saintifik karena tidak sesuai dengan fakta dan data yang diketahui, tidak dapat diuji, dan memiliki kontradiksi internal[8].
Kendati demikian, masih banyak kaum muda, baik Milenial maupun Gen Z[9], yang mempercayai pseudosains. Menurut mereka, zodiak, tarot dan MBTI mampu memberikan validasi terhadap apa yang mereka rasakan dan membantu mereka memahami diri sendiri.
Ini seperti pengakuan Esti (27 tahun) yang menyebut bahwa dia hanya menganggap zodiak sebagai ajang seru-seruan, meski ada poin-poin yang secara personal cocok dengannya. Namun, ia punya sikap berbeda saat menanggapi MBTI. Ia mengaku 80% percaya pada hasil tes MBTI karena banyak yang cocok dengan kepribadiannya. Sementara sisanya 20% ragu karena kadang berubah hasil: misalnya dari INFJ (introverted, intuitive, feeling, dan judging) menjadi ENFJ (extraverted, intuitive, feeling, dan judging).
Haus validasi eksternal
Kepercayaan terhadap pseudosains menandakan kebutuhan individu, khususnya kaum muda masa kini, untuk mendapatkan validasi eksternal[14] atas ‘suara’ yang sebetulnya sudah terkandung di dalam dirinya. Sebab, pseudosains menawarkan hal-hal yang terpersonalisasi[15], sesuatu yang tidak diberikan oleh sains modern: rasa berharga, penting, dan narasi yang membuat nyaman[16] sehingga muncul kalimat “ini aku banget”.
Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap zodiak dan pseudosains lainnya selalu bersifat spektrum—ada yang percaya sedikit, ada yang percaya penuh, ada yang tidak percaya sama sekali.
Buktinya, kontras dengan Olivia dan Esti, Izad (25 tahun) menolak sistem zodiak. Di matanya, zodiak tidak layak dipercayai karena mengabaikan beragam faktor lain yang membentuk karakter dan kepribadian individu, seperti kelas sosial atau lingkungan tempat seseorang tumbuh. Ia juga mengaku jengkel karena merasa ‘dicap’ sebagai bermuka dua hanya karena lahir di bulan yang berzodiak gemini.
Izad menegaskan,
“Sekarang gini, misalnya satu gemini lahir dari keluarga kaya, satu lagi miskin, apakah karakter mereka sama? Kan enggak. Lagi pula itu kan sistem dari Yunani sana ya, kok dibawa-bawa ke sini dan digeneralisir. Zodiak ini nggak peduli konteks, padahal karakter orang kan dibentuk konteks sosial, tempat dia tumbuh, entah di kampung, atau di area urban, dan seterusnya.”
Dampak jangka panjang pseudosains
Kepercayaan atas pseudosains terfasilitasi oleh dorongan naluriah manusia. Itu karena secara evolusioner, otak kita terlatih ribuan tahun untuk mempertahankan hidup[17], alih-alih terlatih untuk menjadi benar dan berpikir rasional. Wajar apabila banyak orang masih terbeli oleh narasi disinformasi, misinformasi, bias-bias, dan non-saintifik. Di ceruk inilah pseudosains mengisi celah dan menyebar lebih cepat[18] dengan mengeksploitasi bias kognitif yang tertanam dalam diri setiap orang.
Riset tahun 2020 dari peneliti pseudosains asal Jepang, Yoshimasa Majima[19], menunjukkan adanya kaitan erat antara penerimaan terhadap pseudosains dengan tipe berpikir tipe satu yang lebih purba, otonom, rentan bias, dan bersifat cepat sekaligus intuitif.
Terlebih lagi, pseudosains juga bekerja lewat mekanisme cultural mimicry[20]—meniru bagian-bagian tertentu dari sains agar lebih dipercaya. Dengan kata lain, pseudosains bekerja dengan meminjam peralatan sains untuk mengemas dirinya dan mendapatkan kepercayaan.
Untuk menangkalnya, seseorang perlu melatih tipe berpikir dua dari tipologi psikolog Daniel Kahneman: berpikir cepat atau lambat. Tipologi dua menuntut kita berpikir lebih lambat, logis, analitis, deliberatif, dan lebih dapat diandalkan[21]. Pasalnya, dampak dari percaya pseudosains dapat menjadi serius seperti penolakan vaksin, sikap anti-sains, stereotipe berdasarkan zodiak, rasisme, narsisisme, hingga mentalitas egosentris dan otoritarian[22].
Dampak terakhir di atas mengacu pada kritik Adorno, filsuf Jerman,[23] yang menyebut bahwa cara berpikir astrologis berpotensi melahirkan fasisme dan otoritarianisme karena mereka condong ke “konformitas”, “kepatuhan”, dan “rasa ditakdirkan-untuk-itu”.
Ini menegaskan perlunya menularkan cara berpikir kritis. Di sini peran media amat krusial. Alih-alih terlalu memberi ruang pada kolom astrologi harian atau mingguan[24], media perlu berperan dalam menarasikan sains secara lebih ramah publik.
References
- ^ memang mengklaim (theconversation.com)
- ^ era Babilonia dan berkembang menjadi 12 simbol zodiak dalam kebudayaan Yunani Klasik (www.routledge.com)
- ^ 80% orang dewasa di seluruh dunia tahu zodiak mereka (theconversation.com)
- ^ nilai bisnis miliaran dolar (www.routledge.com)
- ^ tren membaca tarot, garis tangan (www.kompas.id)
- ^ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) (www.independent.co.uk)
- ^ banyak dikritik (doi.org)
- ^ tidak sesuai dengan fakta dan data yang diketahui, tidak dapat diuji, dan memiliki kontradiksi internal (doi.org)
- ^ baik Milenial maupun Gen Z (www.economist.com)
- ^ bias kognitif (www.sog.unc.edu)
- ^ Barnum effect (www.researchgate.net)
- ^ hanya sesuai dengan selera, nilai-nilai atau kepercayaannya sendiri (search.worldcat.org)
- ^ metamorworks/shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ validasi eksternal (papers.ssrn.com)
- ^ terpersonalisasi (www.nytimes.com)
- ^ narasi yang membuat nyaman (www.insightfultake.com)
- ^ secara evolusioner, otak kita terlatih ribuan tahun untuk mempertahankan hidup (www.apa.org)
- ^ pseudosains mengisi celah dan menyebar lebih cepat (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
- ^ Yoshimasa Majima (www.researchgate.net)
- ^ cultural mimicry (www.researchgate.net)
- ^ lebih dapat diandalkan (search.worldcat.org)
- ^ mentalitas egosentris dan otoritarian (academic.oup.com)
- ^ kritik Adorno, filsuf Jerman, (s3.amazonaws.com)
- ^ kolom astrologi harian atau mingguan (www.instagram.com)
Authors: Muhammad Naufal Waliyuddin, Researcher of Youth and Religious Studies. Doctoral candidate in Islamic studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga