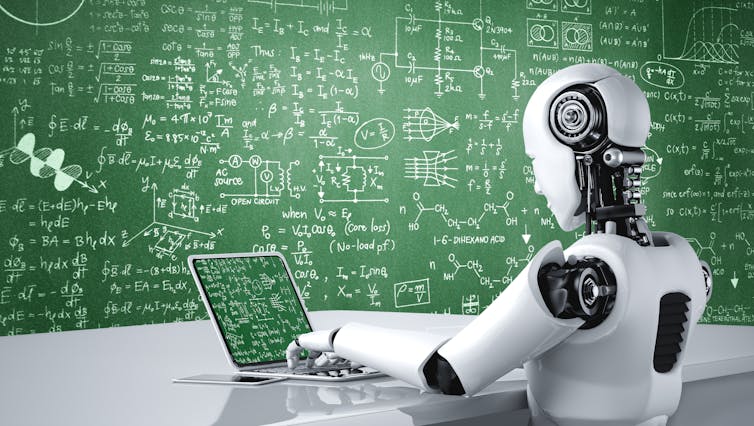Hidup dan mati di tengah ironi ketimpangan infrastruktur Indonesia
- Written by Khalid Walid Djamaludin, Antropolog, University of Latvia

● Infrastruktur tak sekadar benda mati, tapi jadi cerminan perlakuan negara.
● Ketimpangan dan penyelewengan memicu bertumpuknya emosi sehingga memengaruhi sikap rakyat terhadap negara.
● Pemerintah harus mementingkan aspek manusia dalam infrastruktur, bukan capaian angka saja.
Jalan di Sikka, Nusa Tenggara Timur[1] yang seharusnya menghubungkan kehidupan justru menjadi saksi penderitaan Fransiska Seang. Perempuan 23 tahun itu terpaksa melahirkan di tengah perjalanan menuju Puskesmas Bola karena jalan yang rusak parah.
Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu singkat berubah menjadi berjam-jam. Pasalnya, infrastruktur di sana nyaris tak tersentuh pembangunan selama puluhan tahun.
Bidan yang hendak menolong Fransiska baru tiba tiga jam kemudian. Kepala Dinas Kesehatan Sikka, Petrus Herlemus, mengakui bahwa peristiwa semacam ini bukan hal baru. Akses jalan yang buruk dan fasilitas kesehatan yang terbatas sudah lama menjadi bagian dari keseharian warga.
Kisah Fransiska bukan sekadar tragedi. Ia mencerminkan paradoks pembangunan yang gemar merayakan proyek-proyek besar, tapi melupakan jalan kecil tempat kehidupan sehari-hari warga bergantung.
Di tengah gempita pembangunan infrastruktur nasional, masih banyak masyarakat Indonesia yang harus bertaruh nyawa hanya demi bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar.
Infrastruktur sebagai sosial dan politik
Kita acap menganggap infrastruktur sebagai benda mati: jalan, jembatan, atau gedung. Padahal, di balik beton dan aspal tersimpan relasi sosial dan politik yang kompleks. Infrastruktur tidak hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan kekuasaan, kepercayaan, dan harapan publik.
Kajian antropologi kontemporer[2] menegaskan bahwa infrastruktur bukan sekadar sistem teknis, melainkan formasi sosial dan politik yang membentuk kehidupan bersama. Ia menjadi cermin mengenai bagaimana negara hadir dan kadang absen dalam mengatur kehidupan warganya.
Antropolog Dimitris Dalakoglou[3] menunjukkan bahwa bahkan satu jalan pun dapat mengungkapkan suatu perubahan sosial dan politik. Melalui jalan raya lintas batas Albania dan Yunani, ia melihat bagaimana infrastruktur menjadi ruang di mana nasionalisme, migrasi, dan globalisasi saling berkelindan.
Kisah di Sikka memperlihatkan hal serupa. Ketika seorang ibu melahirkan di jalan karena akses yang buruk, masyarakat tidak sekadar menyalahkan takdir. Mereka merefleksikan kekecewaan, kemarahan, sekaligus menilai sejauh mana negara benar-benar hadir di tengah mereka.
Antropolog Hannah Knox dan Evelina Gambino[4] menegaskan bahwa infrastruktur adalah sarana yang membentuk dan merefleksikan kekuasaan negara. Melalui jalan yang rusak atau jembatan yang roboh, masyarakat belajar membaca wajah negara yang mereka alami setiap hari.
Harapan warga yang tak sampai
Di Timor Tengah Utara[5], saya menyaksikan bagaimana warga desa menaruh harapan besar pada pembangunan melalui skema dana desa. Mereka percaya bahwa pembangunan infrastruktur dengan skema tersebut akan membawa perubahan, bahkan kemajuan.
“Saya berharap kepala desa dapat membawa kemajuan. Masyarakat berharap Kepala Desa dapat membangun dengan dana desa,” ujar Antonius (nama disamarkan), warga Timor Tengah Utara.
Sayangnya, mereka justru menyaksikan tumpukan material proyek yang terbengkalai. Renovasi posyandu, pembangunan jalan desa, atau irigasi sering kali berhenti di tengah jalan akibat tata kelola yang buruk.
Misalnya, dana proyek digunakan untuk kepentingan pribadi aparat desa, manipulasi laporan keuangan, atau kontraktor lokal yang dekat dengan kepala desa menerima pembayaran meski pekerjaan belum selesai.
Read more: Politisasi proyek infrastruktur tak terhindarkan, namun kerap tak sejalan dengan kebutuhan publik[6]
Berbagai penyelewengan tersebut membuat sentimen negatif warga bercampur aduk.
Kasus korupsi dan proyek terbengkalai membuat mereka merasa ditinggalkan dan tidak punya suara dalam pembangunan. Sementara rasa malu muncul karena desa mereka sering dijadikan contoh buruk.
Tumpukan material bangunan pun menjadi pengingat kegagalan bersama. Kepercayaan terhadap otoritas juga melemah karena pengelolaan dana yang tertutup dan tidak melibatkan warga.
Alhasil, infrastruktur yang seharusnya membawa kemajuan justru menimbulkan luka sosial. Ia menjadi simbol kekecewaan kolektif dan menunjukkan bahwa pembangunan juga membentuk perasaan, bukan hanya fisik desa.
Respons para warga inilah yang disebut antropolog Hannah Knox sebagai infrastruktur afektif[7] untuk menggambarkan bagaimana masyarakat terlibat secara emosional dan fisik dengan infrastruktur dalam kehidupan sehari-hari.
Jalan yang berlubang, jembatan yang retak, atau listrik yang tak menyala bukan hanya soal teknis, melainkan pengalaman emosional tentang bagaimana negara dirasakan, kadang melalui ketidakhadirannya.
Pendekatan ini menyoroti peran infrastruktur sebagai wadah untuk memunculkan imajinasi politik dan aksi sosial, mengungkap kontinuitas dan keretakan dalam pengalaman sehari-hari proyek negara.
Antara hidup dan mati
Tragedi yang dialami Fransiska bukanlah satu-satunya. Pada September 2025[8], seorang ibu di Desa Pappuring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kehilangan bayinya karena tidak sempat mendapat pertolongan medis akibat jalan rusak dan fasilitas kesehatan yang jauh.
Dua kisah ini menegaskan bahwa infrastruktur dalam bentuknya yang paling nyata dapat menentukan hidup dan mati seseorang.
Selain infrastruktur jalan, cerminan serupa bisa kita lihat dari kasus ambruknya gedung sekolah yang terjadi hampir setiap bulan[9] di berbagai wilayah. Alhasil, banyak anak-anak yang terpaksa libur—hak mereka mengakses pendidikan menjadi terganggu.
Kasus ini menggambarkan betapa timpangnya akses terhadap infrastruktur kesehatan dasar maupun pendidikan di Indonesia. Jangankan mencapai kemakmuran, warga pun mungkin bakal berpikir dua-tiga kali untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
Melalui kasus di atas, sudah saatnya Indonesia berhenti mengukur capaian pembangunan dari panjang aspal atau banyaknya proyek. Pengukurannya harus lebih dalam: Sejauh mana kualitasnya dalam menopang kehidupan mereka yang bergantung padanya.
Narasi pemerintah belakangan ini tampaknya menyederhanakan persoalan infrastruktur menjadi sekadar urusan ekonomi, seperti kelancaran distribusi barang, masuknya pabrik-pabrik, dan aliran investasi. Akibatnya, infrastruktur dinilai dari seberapa banyak uang yang masuk dan proyek yang berhasil dibangun, bukan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Padahal, infrastruktur menjadi cermin bagaimana suatu negara menghargai kemanusiaan. Melalui jalan-jalan yang retak atau infrastruktur yang rusak, kita belajar bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang konektivitas, tetapi tentang keberlanjutan hidup manusia yang melaluinya.
References
- ^ Sikka, Nusa Tenggara Timur (www.youtube.com)
- ^ Kajian antropologi kontemporer (www.dukeupress.edu)
- ^ Antropolog Dimitris Dalakoglou (doi.org)
- ^ Antropolog Hannah Knox dan Evelina Gambino (doi.org)
- ^ Di Timor Tengah Utara (dspace.lu.lv)
- ^ Politisasi proyek infrastruktur tak terhindarkan, namun kerap tak sejalan dengan kebutuhan publik (theconversation.com)
- ^ infrastruktur afektif (doi.org)
- ^ Pada September 2025 (www.youtube.com)
- ^ hampir setiap bulan (www.kompas.id)
Authors: Khalid Walid Djamaludin, Antropolog, University of Latvia