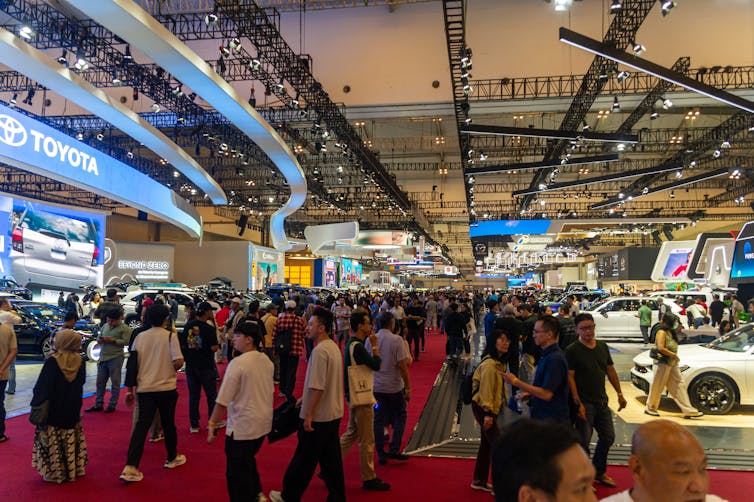Keadilan restoratif dalam KUHP Baru: Ekspektasi tinggi, kesiapan rendah
- Written by Wahyu Saefudin, PhD Researcher, Flinders University
● KUHP baru membawa aturan progresif, tapi Indonesia belum siap menerapkannya.
● Ketidaksiapan petugas dan ketiadaan pedoman berisiko menimbulkan kebingungan.
● Tanpa kesiapan dan ekosistem pendukung, KUHP baru bisa menjadi masalah baru.
Tahun 2026 nanti, tepatnya 2 Januari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang menggantikan Wetboek van Strafrecht[1] (WvS) warisan kolonial Belanda, akan resmi berlaku di seluruh Indonesia.
Ini bukan sekadar momen pergantian undang-undang, melainkan perombakan mendasar. Hukum pidana Indonesia akan segera meninggalkan paradigma retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif (pemulihan), yang juga disebut keadilan restoratif.
Dalam KUHP baru, pemidanaan tidak lagi semata-mata sebagai upaya balas dendam atau menimbulkan penderitaan, melainkan lebih berfokus pada pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan harmoni sosial.
Paradigma keadilan restoratif[2] sepatutnya dapat meningkatkan akses warga terhadap keadilan, khususnya bagi korban kejahatan serta kelompok rentan dan termarginalkan.
Read more: 5 ahli jelaskan apa itu 'restorative justice' dan penerapannya di Indonesia[3]
Perubahan ini pun sejalan dengan tren global[4], yang memprioritaskan beragam opsi pemidanaan untuk menempatkan sanksi penjara sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium).
Contoh alternatif ini terdapat pada Pasal 51 hingga Pasal 54 KUHP baru yang memperkenalkan konsep pemaafan hakim (judicial pardon), sanksi kerja sosial (Pasal 85) dan pengawasan (Pasal 76).
Namun, di balik kebijakan ini, apakah aparat penegak hukum (APH) kita sudah siap menerapkannya?
Perombakan paradigma
Jika KUHP lama secara implisit menekankan efek jera melalui perenggutan kebebasan fisik (penjara), KUHP baru justru membawa perubahan signifikan dalam tujuan pemidanaan.

Misalnya, Pasal 51 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:
(a) mencegah tindak pidana;
(b) memasyarakatkan terpidana;
(c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan; dan
(d) memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Di lapangan, perubahan ini akan berdampak besar bagi APH. Sebab, polisi, jaksa, dan hakim dituntut untuk lebih memiliki kepekaan sosiologis serta kecakapan dalam mediasi konflik.
Artinya, mereka harus berperan aktif dalam memahami latar belakang sebuah tindak pidana secara objektif.

Sayangnya, ada indikasi APH tidak siap menghadapi pergeseran ini. Sebagai contoh, terdapat keterbatasan pemahaman dan kapasitas APH selama ini dalam memahami konsep keadilan restoratif dan pidana alternatif.
Sebagai contoh, keadilan restoratif hanya dipahami sebagai penghentian perkara pidana[7]. Padahal, secara substantif ada tanggung jawab untuk pemulihan korban yang juga harus diperhatikan.
Kerapuhan tulang punggung sistem
Keberhasilan pendekatan restoratif dan pidana alternatif bergantung pada kualitas penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK)[8]. Ini adalah petugas di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Litmas menjadi alat asesmen objektif sekaligus rekomendasi terkait kelayakan seorang terpidana untuk menjalani hukuman di luar penjara.
Sayang, jumlah PK yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Hanya ada 2.851 petugas[9] dari kebutuhan ideal 9.975 orang. Jumlah itu pun dihitung sebelum adanya beban kerja tambahan bagi PK akibat pelaksanaan KUHP baru.
Kekurangan PK menyebabkan beban kerja berlebihan sehingga berisiko menurunkan kualitas Litmas. Selain itu, asesmen dan rekomendasi pidana alternatif dari PK menjadi kurang komprehensif dan berisiko tidak akurat.
Ujung-ujungnya, keadilan restoratif berisiko sulit diterapkan secara substantif, kepercayaan APH melemah, dan tujuan pengurangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) melalui KUHP baru tidak tercapai.
Absennya pengawasan kerja sosial
Pidana kerja sosial adalah inovasi utama dalam KUHP baru untuk mengurangi kelebihan kapasitas[10] di rumah tahanan dan lapas. Namun, pelaksanaannya membutuhkan ekosistem yang kompleks, serta melibatkan pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.
Pidana kerja sosial disebut sebagai inovasi utama karena mengganti penjara dengan kegiatan kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, berbeda dengan pidana penjara yang seluruh prosesnya ditangani oleh negara melalui lembaga pemasyarakatan, pidana kerja sosial justru berlangsung di luar tembok penjara. Inilah yang membuat pelaksanaannya menjadi lebih kompleks.
Dalam pelaksanaannya, membutuhkan dukungan pemda untuk menyediakan tempat dan jenis kegiatan kerja sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta peran Kementerian Sosial untuk memastikan perlindungan dan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku.
Karena melibatkan banyak aktor di luar sistem pemasyarakatan, pidana kerja sosial memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks dibandingkan pidana penjara.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada kesepakatan nasional yang mengikat pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas kerja sosial. Ini memantik sejumlah pertanyaan penting yang kemudian menjadi tantangan:
Di mana nantinya ribuan terpidana kerja sosial akan ditempatkan setiap harinya?
Apakah sudah ada fasilitas umum yang bebas stigma?
Bagaimana mekanisme pengawasan untuk memastikan terpidana benar-benar bekerja selama jam yang ditentukan? Sebab pengawasan secara manual oleh PK dengan kondisi saat ini hampir mustahil.
Bagaimana jika saat sedang bekerja di jalan raya (membersihkan jalan), terpidana mengalami kecelakaan? Bagaimana regulasinya?
Tanpa menjawab pertanyaan ini, pidana kerja sosial berisiko hanya menjadi norma di atas kertas. Aparat akan cenderung menghindarinya akibat ketidakpastian lokasi, pengawasan, dan perlindungan hukum.
Read more: KUHP baru berpotensi memperparah kelebihan kapasitas lapas. Bagaimana bisa?[11]
Risikonya, pilihan pemidanaan akan kembali bertumpu pada penjara. Ini menjauhkan kita dari tujuan KUHP baru untuk mendorong pidana alternatif, melindungi hak terpidana, dan mengurangi overcrowding.
Minimnya pedoman dan risikonya
Keadilan restoratif sebenarnya sudah terlebih dahulu diterapkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)[12] melalui praktik diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) untuk penghentian perkara. Praktik ini dapat memperjelas tugas tiap aparat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
Sayangnya, KUHP baru justru tak menerapkan mekanisme tersebut. Dampaknya, akan terjadi kebingungan besar dalam penanganan perkara.
Katakanlah proses mediasi berjalan dan kesepakatan tercapai. Namun, penyidik, jaksa, dan hakim tidak memiliki aturan bersama yang jelas seperti prosedur dalam UU SPPA.
Read more: Hari Bhakti Adhyaksa: Jaksa Agung dan tantangan penegakan hukum bagi pemerintahan Prabowo[13]
Akibatnya, meskipun mediasi berhasil, perkara tetap bisa berlanjut ke tahap penuntutan atau pemidanaan karena tidak ada rujukan bersama yang memberikan kepastian hukum.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi keadilan restoratif, menurunkan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi, serta mendorong aparat kembali pada pola penegakan hukum yang retributif.
Apa yang harus dilakukan?
Agar KUHP baru benar-benar menghadirkan keadilan yang memulihkan, ada tiga langkah mendesak yang harus menjadi prioritas.
(Tangis keluarga korban Tragedi Kanjuruhan akibat vonis hakim dianggap tidak adil)Pertama, percepatan penyusunan pedoman lintas sektor agar terjadi keseragaman standar operasional, termasuk penghentian perkara pascamediasi.
Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas petugas tidak bisa ditawar. APH harus memetakan kebutuhan jumlah pegawai, sehingga beban kerja petugas tidak berlebihan.
Ketiga, pembangunan ekosistem restoratif berbasis komunitas. Kepedulian masyarakat yang menjadi kekayaan kultural di Indonesia harus dioptimalkan untuk membantu mengatasi kebutuhan sumber daya yang kompleks.
KUHP baru memang menawarkan peluang besar bagi Indonesia. Namun, tanpa kesiapan instrumen hukum, kapasitas petugas, serta ekosistem pendukung, peluang ini dapat memicu berbagai masalah baru.
References
- ^ Wetboek van Strafrecht (wetten.overheid.nl)
- ^ Paradigma keadilan restoratif (www.unodc.org)
- ^ 5 ahli jelaskan apa itu 'restorative justice' dan penerapannya di Indonesia (theconversation.com)
- ^ tren global (www.proquest.com)
- ^ (Muhammad Asytar/Shutterstock) (www.shutterstock.com)
- ^ (Wahyu Saefudin) (www.canva.com)
- ^ penghentian perkara pidana (theconversation.com)
- ^ Pembimbing Kemasyarakatan (PK) (peraturan.bpk.go.id)
- ^ Hanya ada 2.851 petugas (journal.poltekip.ac.id)
- ^ kelebihan kapasitas (jurnalham.komnasham.go.id)
- ^ KUHP baru berpotensi memperparah kelebihan kapasitas lapas. Bagaimana bisa? (theconversation.com)
- ^ UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (journal.poltekip.ac.id)
- ^ Hari Bhakti Adhyaksa: Jaksa Agung dan tantangan penegakan hukum bagi pemerintahan Prabowo (theconversation.com)
Authors: Wahyu Saefudin, PhD Researcher, Flinders University