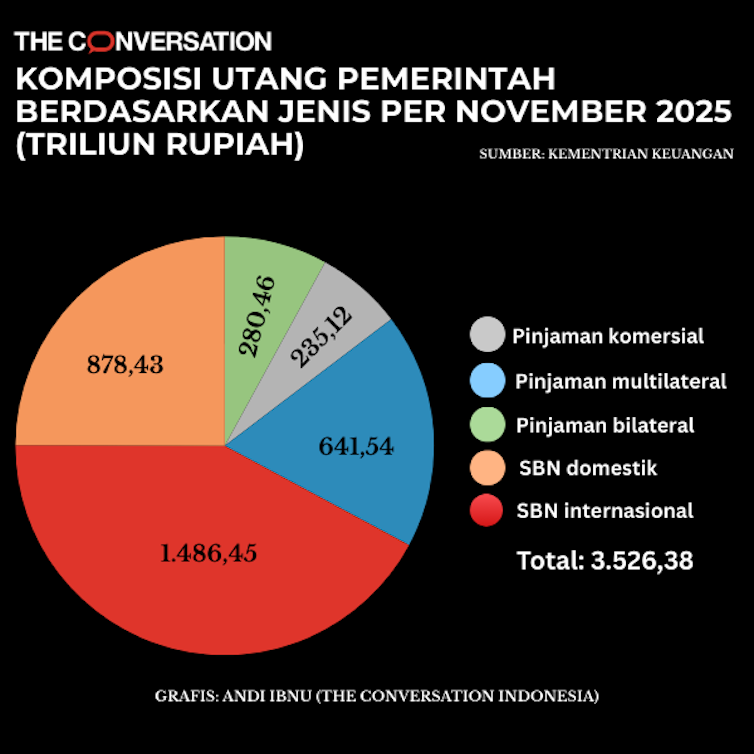Pemilihan Adies Kadir dan risiko keruntuhan independensi MK
- Written by Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation

● Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK mencerminkan upaya politisasi dan sinyal perusakan independensi MK.
● Penujukkan Adies legal secara hukum namun tak bermoral dan tak etis dalam konteks demokrasi.
● Ada masalah dalam aturan seleksi hakim MK, sehingga prosesnya menjadi sangat politis.
Masih ingat Adies Kadir? Politikus Golkar yang beberkan ke publik bahwa anggota DPR mendapatkan tunjangan beras Rp12 juta per bulan dan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta?
Adies, politikus senior Partai Golkar, kini ditetapkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Yang memilihnya tentu saja sejawatnya di DPR RI.
Pemilihan Adies menimbulkan gelombang kritik di kalangan akademisi dan pengamat hukum. DPR memilihnya setelah menganulir keputusan mereka sendiri—yang menetapkan Inosentius Samsul, eks Kepala Badan Keahlian DPR, sebagai calon hakim MK.
Pemilihan Adies pada akhir Januari lalu yang berjalan cepat[1], minim transparansi, dan dinilai lebih mengakomodasi kepentingan politik legislatif dari pada prinsip independensi peradilan.
Dalam konteks tersebut, setiap keputusan yang berpotensi mengikis independensi MK berisiko memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.
Bagaimana akademisi bidang hukum memandang pemilihan Adies sebagai hakim MK? Berikut ini penggalan pernyataan sejumlah pakar dalam diskusi “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK”[2] yang dihelat Constitutional and Administrative Law Society (CALS) di Jakarta pada Jumat (30/1).
Upaya merusak independensi MK
Zainal Arifin Mochtar, Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada
Langkah DPR ini lebih mencerminkan upaya politisasi ketimbang penghormatan terhadap prinsip independensi peradilan, dan merupakan sinyal nyata upaya perusakan independensi MK.
Persoalan utamanya adalah proses seleksi yang tidak dijalankan sesuai ketentuan undang-undang dan membuka ruang kuat bagi kepentingan politik legislatif.
Perubahan calon hakim konstitusi secara tiba-tiba dan tanpa alasan kuat menunjukkan motif politik tertentu yang rentan merusak kredibilitas lembaga dan seakan mengarah pada penguatan konservatif otoritarianisme.
Titi Anggraini, Peneliti Kepemiluan dan Dosen Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia
Proses penetapan hakim MK tidak memenuhi prinsip dasar seleksi terbuka, objektif, transparansi dan partisipasi publik yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam memilih hakim konstitusi.
Pengisian jabatan hakim MK seharusnya bukan urusan segelintir elite politik, melainkan urusan negara yang menyangkut kepentingan republik dan rakyat secara luas, karena kontrak sosial negara dengan rakyat.
Sebagai negara hukum, pengelolaan kekuasaan seharusnya berlandaskan nilai-nilai good governance. Namun DPR sebegitunya menegasikan dan meminggirkan keberadaan publik, seolah seluruh proses hanya menjadi urusan internal para elite politik, tanpa melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Seolah semua-semuanya cuma urusan mereka dan hanya diputuskan dari, oleh, dan untuk mereka.
Legal, tapi tak bermoral
Bivitri Susanti - Dosen Hukum Tata Negara, Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera
Secara formal, penunjukan Adies Kadir oleh DPR merupakan sesuatu yang legal, sah secara hukum. Namun, hal itu tidak otomatis membuatnya wajar, bermoral, atau etis dalam konteks demokrasi dan etika konstitusional.
Kalau pertanyaannya hanya legal atau tidak, jawabannya bisa saja legal. Tapi legal itu belum tentu bermoral.
Menurut aturan, DPR tidak dilarang membatalkan keputusannya sendiri atau membatasi durasi uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi. Namun, tidak adanya aturan hukum yang melarang tersebut bukan berarti DPR boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Proses penggantian calon Hakim MK ini pun janggal. Keputusan yang sudah dibuat sebelumnya, tiba-tiba dibatalkan, lalu dilakukan lagi uji kelayakan yang berlangsung sangat singkat.
Dulu prosesnya tidak seperti ini. Ada fit and proper test yang serius. Ada pendalaman. Sekarang hanya presentasi singkat, lalu diputuskan.
Ini bukan sekadar soal Mahkamah Konstitusi. Pola yang sama pernah terjadi di KPK, lalu menyusul lembaga lain. Demokrasi dilumpuhkan secara perlahan, tapi dengan cara-cara yang tampak sah.
Kita dididik menjadi warga negara yang taat hukum, tetapi kita sering tidak sadar bahwa hukum itu sedang dipakai sebagai senjata untuk mematikan demokrasi.
Kalau lembaga yang seharusnya mengontrol kekuasaan digerogoti, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa kontrol. Itu bukan lagi demokrasi.
Kelompok akademisi dan masyarakat sipil perlu membangun perlawanan melalui narasi kritis, bahkan jalur hukum. Ini karena kekuasaan politik tidak akan runtuh dengan sendirinya. Ia harus diuji, ditantang, dan dipertanggungjawabkan.
Kita harus jujur mengatakan bahwa demokrasi sedang bergeser ke arah otokrasi. Dan sekarang kita berada dalam mode bertahan.
Membuat MK disfungsi
Susi Dwi Harijanti - Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Padjdadjaran
Ada satu disertasi yang ditulis oleh Sebastian Pompe, yang berjudul The Study of Institutional Collapse[3]. Disertasi tersebut berfokus pada institusi Mahkamah Agung.
Dengan kejadian yang sudah dialami MK, terutama yang berkaitan dengan titipan jabatan ini, maka jangan-jangan ini merupakan jalan yang ditempuh atau cara yang ditempuh oleh lembaga-lembaga berwenang untuk melemahkan atau bahkan melakukan disfungsi.
Kalau pun tidak disfungsi secara total, paling tidak Mahkamah Konstitusi akan dibuat tidak bisa berfungsi secara maksimal. Yang dikhawatirkan adalah akan terjadi institutional collapse (keruntuhan kelembagaan), akibat meningkatnya politisasi terhadap lembaga peradilan.
Fungsi MK itu memeriksa dan memutus perkara-perkara politik. Karena itulah MK menjadi target dari terjadinya politisasi.
Sistem yang terlalu politis
Iwan Satriawan - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Akar masalahnya dari awal adalah kita punya masalah dalam proses seleksi hakim MK. Prosesnya diserahkan ke lembaga-lembaga yang mengusulkannya untuk mengaturnya sendiri.
Selain itu, tidak ada komitmen dari pada anggota DPR untuk menempatkan diri sebagai negarawan. Seleksinya too political. Politikus sampai bisa masuk jadi kandidat.
Di negara lain, contohnya Korea Selatan, yang bisa jadi kandidat hanya hakim karier dan ahli hukum, politikus tidak bisa masuk.
Sekarang kita serahkan semua proses ini ke DPR, ya jelas mereka mengangkat teman-teman mereka sendiri. Karakter politikus mereka lebih banyak loyal pada teman-teman sesama parpol, bukan pada konteks konstitusi.
References
- ^ berjalan cepat (news.detik.com)
- ^ “Membongkar Borok Seleksi Hakim MK” (www.instagram.com)
- ^ The Study of Institutional Collapse (www.jstor.org)
Authors: Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation
Read more https://theconversation.com/pemilihan-adies-kadir-dan-risiko-keruntuhan-independensi-mk-275097