3 klasifikasi siswa dalam pendidikan perubahan iklim. Kamu yang mana?
- Written by Kelvin Tang, PhD Candidate, University of Tokyo
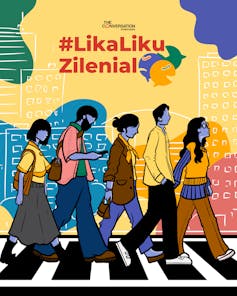
● Kaum muda Indonesia memiliki pemahaman dan sikap yang beragam terhadap perubahan iklim.
● Terdapat tiga kelompok utama yaitu si Ragu, si Pelajar, dan si Advokat.
● Pendidikan perubahan iklim yang efektif harus berpusat pada peserta didik dan sesuai konteks sosial-budaya.
Sudah akrab dengan istilah perubahan iklim[1]?
Isu global yang satu ini bukan sekadar urusan ilmuwan atau pemerintah, tapi juga publik luas, terutama kaum muda. Sebab, mereka lah yang akan menjadi calon pengambil keputusan, inovator, dan pemimpin masa depan yang menghadapi dampak nyata dari krisis iklim.
Tahun ini, saya melakukan survei[2] yang melibatkan 4.501 siswa SMA di empat kota di Indonesia, yakni: Jakarta, Surabaya, Malang, dan Balikpapan. Studi ini bertujuan mengetahui bagaimana siswa memahami isu perubahan iklim, dengan mengacu pada tiga dimensi:[3] kognitif (pengetahuan), afektif (sosio-emosi), dan perilaku.
Hasilnya, para siswa dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar: si Ragu (The Uncertain) sebanyak 26%, si Pelajar (The Learners) sebanyak 47%, dan si Advokat (The Advocates) sebanyak 27%. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan iklim yang berbeda pula.
Si ‘Ragu’ yang membutuhkan pemantik emosional
Hasil survei menunjukkan, kelompok si Ragu memiliki tingkat pengetahuan, kepedulian, serta kesiapan bertindak yang relatif rendah. Mereka bercirikan:
-
Cukup tahu soal perubahan iklim, tapi skor rata-rata pengetahuan faktualnya hanya 43 dari 100.
83% siswa masih keliru menganggap penipisan lapisan ozon[4] sebagai penyebab utama perubahan iklim. Mereka memahami perubahan iklim hanya sebagai peningkatan suhu bumi.
Salah menilai efektivitas aksi mitigasi. Daur ulang rumah tangga dianggap lebih penting ketimbang pengurangan limbah makanan dan perencanaan keluarga, padahal dua opsi terakhir berdampak lebih besar.
Tingkat kepedulian masih rendah. Mereka cenderung netral atau apatis terhadap isu ini, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas.
Harapan terhadap solusi rendah, terutama jika menyangkut kepercayaan terhadap pemimpin politik.
Cenderung pasif karena kurang inisiatif untuk bertindak dan rasa percaya diri rendah.
Kelompok ini perlu pemantik emosional agar bisa terhubung secara personal dengan isu iklim. Pendidikan berbasis seni[5] (art-based learning), seperti menulis puisi, membuat poster, atau drama bertema lingkungan, bisa menjadi pintu masuk.
Sebuah eksperimen di Portugal[6] membuktikan bahwa pembelajaran perubahan iklim berbasis seni bisa meningkatkan keterlibatan emosional dan bisa mengubah pola pikir siswa.
Kisah inspiratif dari sesama anak muda[7] atau pengalaman komunitas lokal juga efektif membangun empati dan keterlibatan.
Guru bisa memutar video pendek tentang siswa di daerah lain yang memulai gerakan mengurangi sampah makanan atau mengundang relawan muda dari komunitas lingkungan setempat untuk berbagi pengalaman mereka di kelas.
Setelah ketertarikan tumbuh, edukasi bisa dilanjutkan dengan memberikan pengetahuan dasar yang sistematis tentang sebab, dampak, dan solusi perubahan iklim melalui modul interaktif, kuis, atau kegiatan diskusi kelompok yang dipandu oleh guru.
Memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik dibanding si Ragu, tapi masih mengalami miskonsepsi.
Merasa paham tentang isu perubahan iklim, tapi belum benar-benar memahaminya secara ilmiah.
Bersikap sangat positif terhadap perubahan iklim. Sadar bahwa perubahan iklim adalah ancaman serius dan menunjukkan kepedulian tinggi, khususnya terhadap dampak pada diri dan keluarga.
Sebagian masih ragu terhadap solusi jangka panjang, terutama yang bergantung pada kebijakan politik.
Bersedia menghemat energi, mengurangi konsumsi, dan belajar mengenai perubahan iklim lebih jauh.
Masih banyak yang tidak yakin apakah tindakan mereka akan berdampak.
Kelompok ini cocok dengan pembelajaran berbasis inkuiri atau pemecahan masalah[8] (inquiry-based/problem-based learning) yang mendorong penyelidikan aktif dan pemahaman ilmiah yang lebih mendalam.
Studi kasus dan penelusuran informasi melalui media bisa menjadi strategi pendidikan perubahan iklim[9] yang membantu mereka mengaitkan teori dengan kehidupan nyata. Guru bisa mengajak siswa menelusuri berita banjir di kota mereka dan kemudian menghubungkannya dengan isu krisis iklim global, atau membandingkan laporan organisasi iklim dunia seperti IPCC[10] dengan liputan media lokal.
Selain itu, siswa bisa disuguhi contoh konkret dan kisah sukses, seperti sekolah di Kepulauan Banda[11] yang berhasil bebas plastik berkat inisiatif siswa dan guru. Kisah-kisah ini bisa menumbuhkan harapan dan membangun keyakinan bahwa kontribusi sekecil apa pun tetap berarti.
Si ‘Advokat’ yang siap beraksi
Kelompok ini memiliki pengetahuan yang lebih komplit, punya kepedulian tinggi, dan motivasi besar untuk bertindak. Karakteristiknya adalah sebagai berikut:
Memiliki pemahaman konseptual yang paling tajam meski nilai pengetahuan faktual belum tinggi.
Mampu membedakan tindakan yang berdampak lebih akurat daripada kelompok lain.
Memahami isu iklim sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan.
Sangat peduli terhadap perubahan iklim dan dampaknya, tidak hanya pada level individu tetapi juga kolektif.
Menunjukkan harapan yang konstruktif, yaitu keyakinan bahwa melalui kerja sama, perbaikan masih mungkin terjadi.
Siap beraksi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun melalui kampanye, petisi, atau advokasi kebijakan.
Memiliki keyakinan tinggi terhadap aktivitas manusia sebagai penyebab perubahan iklim, tapi tetap skeptis terhadap strategi mitigasi perubahan iklim.
Pendekatan terbaik bagi mereka adalah pembelajaran berbasis proyek[12] (project-based learning) yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang solusi, baik di sekolah maupun komunitas. Mereka bisa dilibatkan dalam proyek jangka panjang, kampanye, kompetisi, atau kerja sama lintas sekolah.
Si Advokat juga bisa dilatih menjadi fasilitator atau peer educators untuk membimbing teman sekelas atau adik kelas dalam diskusi sederhana tentang gaya hidup ramah iklim. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas kepemimpinan, tetapi juga menumbuhkan semangat aktivisme.
Fokus pada peserta didik
Ketiga kelompok di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang cocok untuk semua siswa. Pendidikan perubahan iklim harus dirancang ulang agar adaptif dan responsif terhadap keragaman karakteristik peserta didik.
Pendekatan yang berpusat pada peserta didik[13] (learner-centred)—berakar pada konteks lokal, nilai, dan realitas sosial-budaya siswa—menjadi kuncinya.
Pendidikan perubahan iklim[14] sebaiknya tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran, empati, dan kapasitas untuk bertindak.
Dengan memahami karakter siswa lebih dalam, kita bisa menumbuhkan generasi yang tidak hanya paham krisis iklim, tetapi juga siap menjadi bagian dari solusinya.
References
- ^ perubahan iklim (www.un.org)
- ^ Tahun ini, saya melakukan survei (doi.org)
- ^ tiga dimensi: (unesdoc.unesco.org)
- ^ penipisan lapisan ozon (science.nasa.gov)
- ^ Pendidikan berbasis seni (link.springer.com)
- ^ Sebuah eksperimen di Portugal (doi.org)
- ^ Kisah inspiratif dari sesama anak muda (subjecttoclimate.org)
- ^ pembelajaran berbasis inkuiri atau pemecahan masalah (www.oce.global)
- ^ strategi pendidikan perubahan iklim (doi.org)
- ^ organisasi iklim dunia seperti IPCC (www.ipcc.ch)
- ^ sekolah di Kepulauan Banda (lighthouse-foundation.org)
- ^ pembelajaran berbasis proyek (www.pblworks.org)
- ^ Pendekatan yang berpusat pada peserta didik (unesdoc.unesco.org)
- ^ Pendidikan perubahan iklim (doi.org)
Authors: Kelvin Tang, PhD Candidate, University of Tokyo



