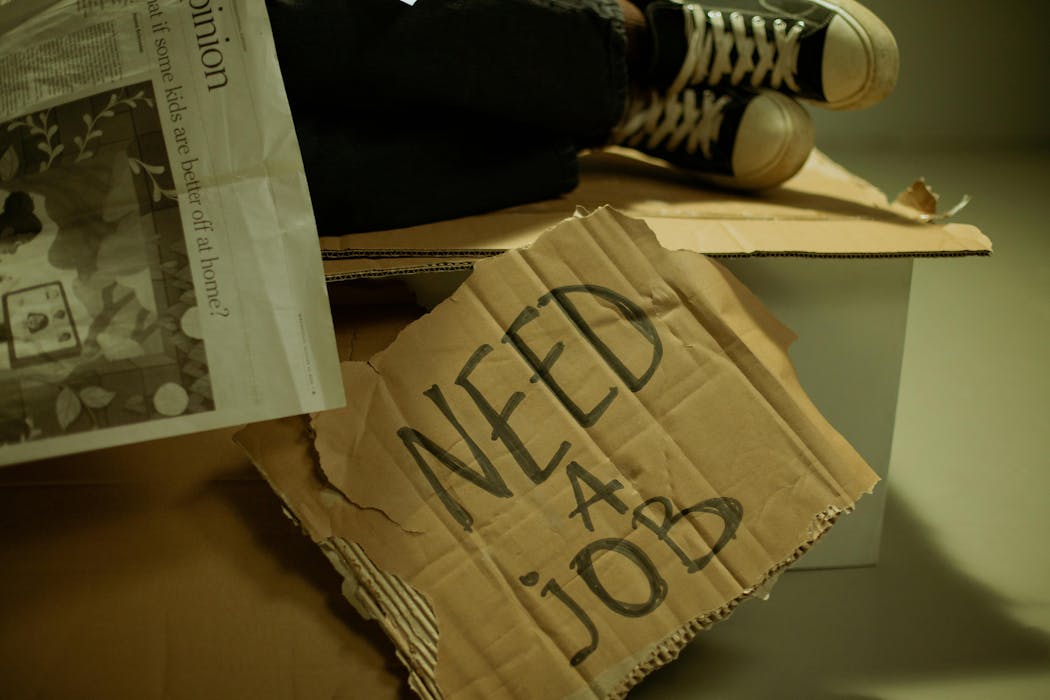Trauma lama, solidaritas baru: Publik makin waspada melawan provokasi anti-Tionghoa saat gejolak politik
- Written by Charlotte Setijadi, Lecturer in Asian Studies, The University of Melbourne
● Provokasi anti-Tionghoa di tengah kerusuhan akhir Agustus lalu memantik trauma Mei 1998.
● Publik melawan kampanye provokasi berbasis etnis dengan saling menjaga, berbagi informasi, dan menuai solidaritas digital.
● Solidaritas perlu dipupuk agar masyarakat tidak mudah dipecah-belah.
Dalam gelombang demonstrasi anti-pemerintah dan ketegangan politik pada akhir Agustus hingga awal September silam, media sosial dan platform WhatsApp sempat marak dengan berbagai kampanye misinformasi dan disinformasi yang menargetkan masyarakat Tionghoa Indonesia[1].
Bagi banyak warga Tionghoa, narasi anti-Tionghoa yang beredar dalam pesan-pesan viral ini membangkitkan kembali ingatan traumatis tentang Tragedi Mei 1998[2]. Ini sekaligus memicu ketakutan baru bahwa mereka sekali lagi akan dijadikan kambing hitam di tengah krisis politik dan sosial.
Meskipun terdapat banyak kemiripan dengan pola provokasi dan narasi anti-Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998, ada satu hal yang berbeda kali ini: munculnya gerakan solidaritas antar-etnis.
Ini tercermin di tagar media sosial seperti #WargaJagaWarga yang bertujuan meredam provokasi, termasuk yang bersentimen etnis.
Mengapa trauma itu ada?
Sentimen anti-Tionghoa mulai meningkat pada bulan-bulan menjelang kerusuhan Mei 1998. Ketika ekonomi Indonesia kolaps akibat Krisis Keuangan Asia, etnis Tionghoa disalahkan atas berbagai hal, mulai dari kenaikan harga sembako hingga pelarian modal ke luar negeri.
Rezim Suharto dengan senang hati membiarkan narasi-narasi yang mengambinghitamkan etnis Tionghoa dalam krisis ekonomi tersebut.

Setelah Tragedi Mei 1998, investigasi oleh pihak dari dalam[4] maupun luar negeri mengungkap bahwa kekerasan tampak disponsori oleh negara[5] dan dijalankan secara sistematis dengan perencanaan ala militer.
Bagi etnis Tionghoa, Tragedi Mei 1998 mengonfirmasi ketakutan bahwa mereka akan selalu menjadi target amarah massa kala krisis politik. Oleh karena itu, muncul persepsi di antara banyak warga Tionghoa bahwa mereka harus bisa melindungi diri sendiri.
Sementara di era Reformasi, penghapusan kebijakan asimilasi Orde Baru memperbesar ruang kebangkitan budaya dan identitas Tionghoa[6].
Meski demikian, trauma kolektif akibat Tragedi Mei 1998[7] dan berbagai serangan anti-Tionghoa di masa lalu tetap ada dan selalu muncul setiap kali ada gejolak sosial atau politik.
Sebagai contoh, seusai aksi demonstrasi anti-Ahok (Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI saat itu) pada 4 November 2016, sejumlah massa mendatangi kawasan hunian mayoritas Tionghoa[8] di Jakarta Utara tempat Ahok dan keluarganya tinggal. Mereka mengancam akan membakar kompleks tersebut.

Retorika anti-Tionghoa yang disebarkan melalui media sosial juga menguat dalam bulan-bulan berikutnya. Ini menimbulkan kecemasan di kalangan warga Tionghoa bahwa Tragedi Mei 1998 bisa saja terulang kembali.
Tidak mengherankan jika ketakutan warga Tionghoa kembali mencuat saat pesan-pesan misinformasi dan disinformasi bernuansa anti-Tionghoa kembali beredar di tengah gejolak politik terbaru.
Di tengah unjuk rasa dan kerusuhan beberapa bulan lalu, banyak unggahan dan pesan-pesan bergaya psy-ops (operasi psikologis) yang menargetkan etnis Tionghoa beredar di WhatsApp dan Signal.
‘Berita-berita’ palsu tentang penjarahan, imbauan keamanan[9], penculikan, dan kekerasan seksual yang menargetkan warga Tionghoa[10] bermunculan. Sulit membedakan sumber informasi mana yang bisa dipercaya.
Tujuan dari pesan-pesan disinformasi ini jelas: menebar ketakutan, memperdalam ketidakpercayaan antar-etnis, memecah-belah solidaritas masyarakat, dan mengalihkan perhatian publik dari isu sebenarnya, yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Solidaritas antaretnis
Awalnya, kemunculan provokasi-provokasi anti-Tionghoa ini sempat membuat panik dan memperkeruh keadaan.
Namun, masyarakat—terutama kaum muda—kini lebih kritis terhadap narasi yang memecah-belah dan juga lebih waspada terhadap sumber informasi.
Read more: Apakah Generasi Z lebih tahan hoaks ketimbang Gen X dan Gen Y?[11]
Di media sosial, tagar viral seperti #WargaJagaWarga muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap provokasi. Lebih lagi, kampanye digital, jejaring komunitas sipil antaretnis, dan mobilisasi organisasi-organisasi akar rumput berupaya untuk meneduhkan situasi panas, memeriksa fakta, dan melindungi kelompok minoritas[12], termasuk masyarakat Tionghoa.
Contoh solidaritas bisa kita lihat di kawasan Glodok, Jakarta Barat—salah satu daerah target Kerusuhan Mei 1998[13]. Aktivis Charlenne Kayla Roeslie (kontributor artikel ini), melaporkan bahwa gabungan komunitas lokal saling bertukar informasi nomor-nomor darurat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi akar rumput yang bisa diandalkan apabila kekacauan/kerusuhan terjadi.
Anak-anak muda yang lebih memahami teknologi membantu generasi yang lebih tua untuk memverifikasi informasi di media sosial.
Di media sosial, unggahan viral seperti Surat Cinta Untuk Minoritas, Dari Minoritas[14] yang dipelopori oleh influencers Tionghoa seperti Okki Sutanto dan Jenny Jusuf mengajak warga Tionghoa untuk tidak terpancing narasi-narasi yang memecah belah solidaritas antar-etnis. Mereka mengimbau netizen agar tetap berfokus menuntut pemerintahan yang lebih baik.
Untungnya, krisis politik yang terakhir ini tidak berkembang menjadi kerusuhan dan kekerasan seperti skala Tragedi Mei 1998.
Tidak ada penyerangan massal terhadap etnis Tionghoa. Meski hingga kini pemerintah belum memenuhi banyak tuntutan rakyat, situasi politik sudah mendingin.
Pelajaran penting
Pergerakan seperti #WargaJagaWarga memperlihatkan bahwa solidaritas digital antaretnis bisa dilihat sebagai strategi resistensi politik masyarakat sipil. Disinformasi dan narasi berbasis kebencian justru memicu solidaritas dan kewaspadaan bersama.
Platform digital memang berisiko memperlebar polarisasi[15]. Keterlibatan influencers[16] dalam pergerakan politik juga menuai kritik[17].
Namun, munculnya generasi muda dan influencers sebagai aktor penting dalam menjaga hubungan antaretnis adalah fenomena yang memantik harapan untuk masa depan kebinekaan dan demokrasi Indonesia.
Read more: Tipu daya populisme Prabowo: Memperkuat polarisasi, menghilangkan oposisi[18]
Fakta bahwa narasi anti-Tionghoa muncul di tengah kerusuhan kemarin menunjukkan bahwa penebar perpecahan sangat memahami “kekuatan” sentimen anti-Tionghoa sebagai alat untuk memprovokasi massa di Indonesia.
Apakah momentum solidaritas digital yang kita lihat kemarin bisa menjadi pijakan bagi hubungan antaretnis yang lebih kuat di masa depan?
Untuk mencapai dampak yang berkelanjutan, aktor-aktor masyarakat sipil lintas-etnis perlu terus bekerja sama. Kita perlu saling mengingatkan untuk tidak membiarkan provokasi berbau rasial mengalihkan fokus dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik bagi rakyat.
Penulisan artikel ini dibantu oleh saran dan materi dari Charlenne Kayla Roeslie, jurnalis lepas dan aktivis komunitas akar rumput di Glodok, Jakarta.
References
- ^ menargetkan masyarakat Tionghoa Indonesia (theconversation.com)
- ^ membangkitkan kembali ingatan traumatis tentang Tragedi Mei 1998 (theconversation.com)
- ^ (B.J. Habibie: 72 Days as Vice President/Wikimedia) (commons.wikimedia.org)
- ^ dari dalam (perpustakaan.elsam.or.id)
- ^ disponsori oleh negara (indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au)
- ^ memperbesar ruang kebangkitan budaya dan identitas Tionghoa (www.aljazeera.com)
- ^ trauma kolektif akibat Tragedi Mei 1998 (www.bbc.com)
- ^ mendatangi kawasan hunian mayoritas Tionghoa (www.cambridge.org)
- ^ imbauan keamanan (x.com)
- ^ kekerasan seksual yang menargetkan warga Tionghoa (www.instagram.com)
- ^ Apakah Generasi Z lebih tahan hoaks ketimbang Gen X dan Gen Y? (theconversation.com)
- ^ melindungi kelompok minoritas (www.instagram.com)
- ^ daerah target Kerusuhan Mei 1998 (www.theguardian.com)
- ^ Surat Cinta Untuk Minoritas, Dari Minoritas (www.instagram.com)
- ^ memperlebar polarisasi (theconversation.com)
- ^ Keterlibatan influencers (indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au)
- ^ menuai kritik (www.tempo.co)
- ^ Tipu daya populisme Prabowo: Memperkuat polarisasi, menghilangkan oposisi (theconversation.com)
Authors: Charlotte Setijadi, Lecturer in Asian Studies, The University of Melbourne