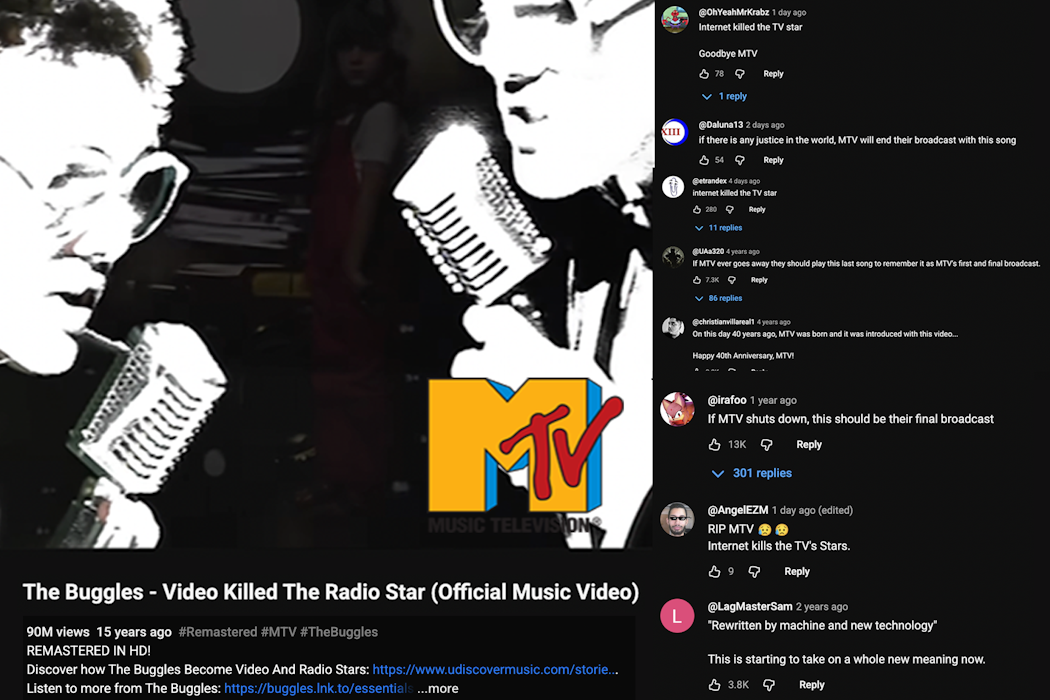Aktivisme kelas menengah: Sempat redup, kini bangkit melawan rezim
- Written by Asep Muizudin Muhamad Darmini, Lecturer in Digital Transformation, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

● Pada gelombang demo Agustus lalu, kesadaran politik kelas menengah kembali bangkit setelah sebelumnya sempat redup.
● Titik baliknya adalah kesadaran bahwa situasi ekonomi telah memukul semua lapisan masyarakat.
● Aktivisme kelas menengah perlu diperkuat melalui solidaritas antarkelas agar tak performatif.
Masih ingat istilah kelas menengah ‘ngehe’[1]?
Istilah yang mulai viral pada 2016 ini menggambarkan perilaku kelas menengah yang apolitis, oportunis, dan pragmatis.
Tahun 2025 ini, seiring dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)[2] serta kembalinya otoritarianisme ala Orde Baru[3], kesadaran politik kelas menengah kembali bangkit.
Dalam demonstrasi terakhir pada Agustus lalu, kita bisa melihat bagaimana masyarakat dari segala latar belakang[4] sosial-ekonomi bersama-sama turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
Namun, seiring dengan meredanya arus demonstrasi tersebut, kritik bermunculan terhadap aktivisme kelas menengah tahun 2025 yang dinilai sekadar berada di level performatif.
Read more: Demonstrasi besar-besaran di Indonesia: pentingnya menanggapi tuntutan rakyat[5]
Gerakan ini dianggap eksklusif dan terpisah dari gerakan kelas pekerja yang lebih luas. Aktor dalam aktivisme performatif ini dianggap bertujuan meningkatkan reputasi pribadi semata.[6][7]
Suara kelas menengah sempat redup
Pada 2024, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan[8] mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang menghabiskan Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per bulan. Kelas menengah terutama ditandai dengan pencapaian pendidikan tinggi[9] dan pendapatan yang stabil melalui pekerjaan formal.
Kelas menengah biasanya memiliki pola pikir ingin mendapatkan pekerjaan stabil setelah meraih kualifikasi pendidikan tinggi. Ini membuat mereka sering kali menjadi subjek kontrol intelektual dan material[11].
Dalam struktur masyarakat neoliberal yang kompetitif, posisi sebagai kelas menengah berpendidikan meniscayakan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan material,[12] dan menihilkan peran-peran intelektual kelas menengah di ruang publik.
Di Indonesia, kecenderungan ini erat kaitannya dengan privatisasi pendidikan tinggi di era Reformasi.
Meredupnya suara aktivis kelas menengah berawal dari perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN)—yang pernah menjadi kiblat aktivisme mahasiswa—menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN)[13] pada tahun 2000.
Perubahan ini telah mengubah lanskap aktivisme mahasiswa secara radikal.
PTN BHMN di era Reformasi diberikan otonomi penuh[14] dalam hal keuangan dan cenderung membebankan pembiayaan pendidikan tinggi kepada mahasiswa.
Konsekuensinya, PTN BHMN jadi cenderung beorientasi profit[15], tidak lagi bersahabat dengan calon mahasiswa dari latar belakang sosial-ekonomi menengah ke bawah.
Dengan demikian, mobilitas sosial-ekonomi yang sebelumnya dapat dilakukan melalui pendidikan tinggi, kini hanya berputar di kalangan kelas menengah saja[16]. Ini perlahan mematikan kesadaran kelas dan solidaritas antar kelas.
Fokus pendidikan tinggi sejak era PTN BHMN telah bergeser menjadi alat untuk mendapatkan pekerjaan, tidak lagi menjadi medium membangun kesadaran sosial dan politik.
Read more: Individualisme yang berlebihan lemahkan kesadaran politik kaum terdidik[17]
Puncak dari dampak privatisasi pendidikan tinggi ini adalah lebarnya kesenjangan antara milenial berpendidikan tinggi dan yang tidak berpendidikan.
Laporan mengenai kesenjangan kehidupan millennial di Jakarta[18] menemukan bahwa milenial berpendidikan tinggi—sebagai bagian dari kelas menengah atas—menikmati pekerjaan bergaji tinggi di sektor ekonomi digital.
Sementara milenial yang tidak berpendidikan tinggi harus berjuang bertahan hidup di Jakarta dengan penghasilan rata-rata Rp1,5 juta per bulan.
Kembalinya kesadaran politik kelas menengah
Memasuki 2024 hingga saat ini, kondisi ekonomi memukul semua kalangan, termasuk mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.
Buktinya, sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 44.433 pekerja[19] mengalami pemutusan hubungan kerja. Fenomena ini merata dari mulai sektor manufaktur hingga media[20].
Menyusul tren global PHK[21] di sektor ekonomi digital, pekerja prekariat[22] di Indonesia juga bernasib sama.
Dalam sebuah wawancara dengan Rory Asyari, jurnalis dan reporter TV, jurnalis senior Marissa Anita[23] membagi pengalaman pahitnya ketika diberhentikan dari SEA Today[24], satu-satunya kanal televisi berbahasa Inggris di Indonesia.
Marissa dan jutaan kelas menengah Indonesia[26] termasuk dalam kategori kelompok yang lebih rentan turun (jatuh miskin)[27] daripada naik kelas sosial.
Sementara itu, jika generasi milenial terdidik sempat merasakan pasar kerja yang lebih stabil, Generasi Z (Gen Z) yang ikut terdampak oleh krisis ekonomi dan politik di Indonesia justru mengalami persaingan ganda. Mereka bersaing dengan generasinya sendiri dan pekerja milenial berpengalaman yang harus kembali berjuang di pasar kerja.
Read more: Pengangguran muda Indonesia sebanyak 17,3%: Penciptaan lapangan kerja makin bermasalah?[28]
Dengan tantangan ekonomi sebesar itu, energi aktivisme kelas menengah perlu dibagi rata dengan kondisi ekonomi digital[29] saat ini yang tidak menjanjikan stabilitas pekerjaan bagi kelas menengah berpendidikan tinggi.
Kelindan antara kesadaran bahwa situasi ekonomi terkini telah memukul semua lapisan masyarakat dengan situasi politik yang menuju ke arah otoritarianisme,[30] menjadi titik balik kembalinya kesadaran kelas dan solidaritas antar kelas di tahun 2025.
Perlu terus dipupuk
Kita perlu mengapresiasi gerakan-gerakan dan aksi protes sebagai potensi oposisi alternatif, mengingat saat ini kita berhadapan dengan struktur pemerintahan yang tidak memiliki oposisi.
Geliat pergerakan ini perlu dilihat bukan sebagai sprint (lari cepat), melainkan sebagai maraton.[31] Sebagaimana maraton pada umumnya[32], daya tahan aktivisme kelas menengah perlu dipupuk terus menerus melalui kesadaran kelas dan solidaritas antarkelas.
Dengan demikian, aktivisme kelas menengah yang pada awalnya hanya dinilai performatif dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan bertransformasi menjadi aktivisme yang benar-benar berguna bagi kemaslahatan bersama.
References
- ^ kelas menengah ‘ngehe’ (news.detik.com)
- ^ pemutusan hubungan kerja (PHK) (www.beritasatu.com)
- ^ kembalinya otoritarianisme ala Orde Baru (eastasiaforum.org)
- ^ masyarakat dari segala latar belakang (www.kompas.id)
- ^ Demonstrasi besar-besaran di Indonesia: pentingnya menanggapi tuntutan rakyat (theconversation.com)
- ^ eksklusif dan terpisah (indoprogress.com)
- ^ meningkatkan reputasi pribadi semata. (kumparan.com)
- ^ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (klc2.kemenkeu.go.id)
- ^ pencapaian pendidikan tinggi (fulcrum.sg)
- ^ Ronin The Poetic Junkies/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ subjek kontrol intelektual dan material (scholarhub.ui.ac.id)
- ^ fokus terhadap pemenuhan kebutuhan material, (scholarhub.ui.ac.id)
- ^ Badan Hukum Milik Negara (BHMN) (www.djkn.kemenkeu.go.id)
- ^ otonomi penuh (hukor.ugm.ac.id)
- ^ beorientasi profit (korpusipb.com)
- ^ kalangan kelas menengah saja (www.thejakartapost.com)
- ^ Individualisme yang berlebihan lemahkan kesadaran politik kaum terdidik (theconversation.com)
- ^ kesenjangan kehidupan millennial di Jakarta (www.thejakartapost.com)
- ^ 44.433 pekerja (economy.okezone.com)
- ^ sektor manufaktur hingga media (www.tempo.co)
- ^ tren global PHK (www.businessinsider.com)
- ^ pekerja prekariat (journals.sagepub.com)
- ^ Marissa Anita (www.youtube.com)
- ^ SEA Today (www.instagram.com)
- ^ FarisFitrianto/Shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ jutaan kelas menengah Indonesia (www.cnbcindonesia.com)
- ^ lebih rentan turun (jatuh miskin) (www.tempo.co)
- ^ Pengangguran muda Indonesia sebanyak 17,3%: Penciptaan lapangan kerja makin bermasalah? (theconversation.com)
- ^ kondisi ekonomi digital (celios.co.id)
- ^ menuju ke arah otoritarianisme, (eastasiaforum.org)
- ^ bukan sebagai sprint (lari cepat), melainkan sebagai maraton. (www.instagram.com)
- ^ maraton pada umumnya (www.jstor.org)
Authors: Asep Muizudin Muhamad Darmini, Lecturer in Digital Transformation, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Read more https://theconversation.com/aktivisme-kelas-menengah-sempat-redup-kini-bangkit-melawan-rezim-267016