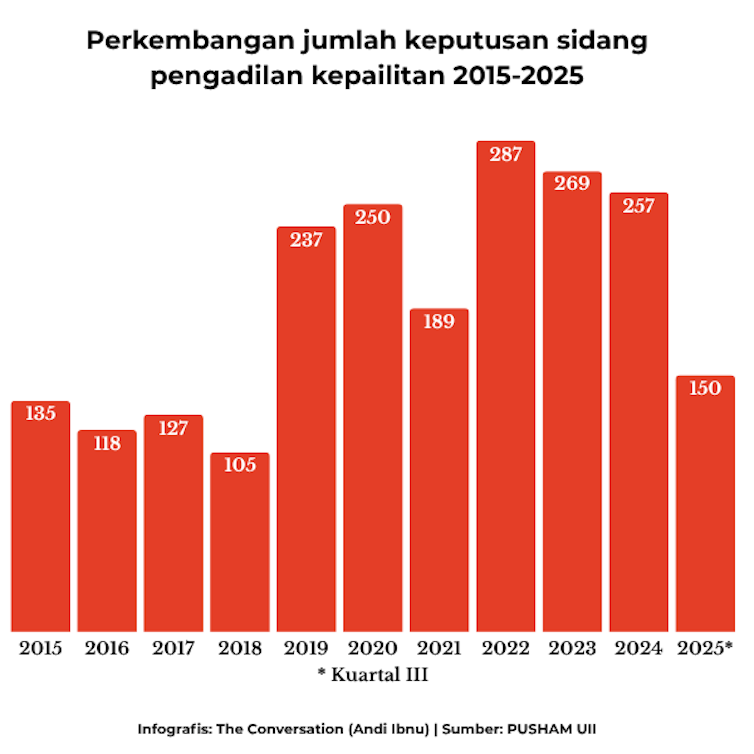Hadapi rentannya emosi remaja, sekolah perlu kembangkan ekosistem empati
- Written by Charyna Ayu Rizkyanti, Dosen Psikologi Perkembangan, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
● Kasus kekerasan dan kematian remaja mencerminkan kegagalan sekolah membaca dan merespons kesehatan mental siswa.
● Indonesia perlu mengembangkan ekosistem empati sesuai konteks budaya agar sekolah mampu menjadi ruang aman.
● Empati dapat dibangun sebagai kompetensi inti melalui kurikulum hingga pelatihan guru.
Kasus ledakan bom di SMA 72 Jakarta[1] dan kematian tragis mahasiswa Universitas Udayana[2] yang terjadi dalam periode berdekatan menunjukkan satu pola besar dalam pendidikan Indonesia, yaitu kegagalan sistemik dalam membaca, memahami, dan merespons kesehatan mental remaja dan mahasiswa.
Penelusuran polisi menunjukkan bahwa remaja pelaku peledakan tersebut sering merasa sendiri, tidak memiliki tempat berkeluh kesah[3], dan terpapar konten digital ekstrem yang mengglorifikasi pelaku kekerasan.
Ini menegaskan pernyataan WHO bahwa kesepian kronis (chronic loneliness) meningkatkan risiko[4], seperti depresi, perilaku agresif impulsif, ideasi berbahaya, dan ketertarikan pada konten ekstrem sebagai bentuk pelarian psikologis.
Read more: Bahaya ide bunuh diri pada remaja bila terlambat ditangani[5]
Kondisi ini diperparah dengan adanya emotional misalignment, yakni ketidakselarasan dalam memahami pesan emosional remaja. UNICEF mencatat[6] bahwa banyak remaja tidak mencari pertolongan bukan karena tidak ingin dibantu, tetapi karena merasa tidak ada orang dewasa yang dapat memahami cara mereka berkomunikasi.
Pengalaman emosional siswa sering terabaikan

Di lingkungan sekolah, budaya pendidikan yang menempatkan prestasi sebagai indikator utama keberhasilan membuat pengalaman emosional siswa sering kali dianggap tidak relevan.
Padahal, riset tahun 2024[8] menunjukkan bahwa tanpa memperhatikan kesejahteraan psikologis (well-being), sekolah tidak punya cukup informasi maupun kedekatan untuk mengenali tanda-tanda awal masalah, sehingga sulit mencegah krisis dan mendukung perkembangan remaja secara utuh.
Karena itu, sekolah perlu mengembangkan ekosistem empati. Penelitian tahun 2024 di Cina[9] menunjukkan bahwa empati dapat menjadi pelindung dinamika sosial remaja.
Empati bukan sekadar kapasitas emosional, tetapi kemampuan perkembangan yang memengaruhi bagaimana remaja membaca situasi sosial[10], merespons konflik, dan memutuskan apakah mereka diam atau bertindak ketika melihat ketidakadilan.
Empati sebagai kompetensi inti pendidikan
Negara-negara Skandinavia sudah lama menempatkan kesejahteraan emosional sebagai fondasi pendidikan. Di Finlandia, misalnya, program KiVa[11] membuktikan bahwa pembelajaran empati berbasis sistemik dapat menurunkan bullying hingga 50% dalam dua tahun.
KiVa menekankan[12] pada literasi emosi, relasi sosial positif, intervensi berbasis komunitas, dan pengawasan psikososial yang berkelanjutan.
Sementara di Denmark, “belajar empati” bukan sekadar kegiatan tambahan tetapi bagian reguler dari jadwal sekolah yang sudah ada sejak 1993. Di sini, siswa antara usia 6 hingga 16 tahun mengikuti sesi yang disebut klassens tid (waktu kelas)[13], di mana mereka membicarakan masalah kelas, perasaan, konflik sosial, atau isu interpersonal dengan mempertimbangkan posisi orang lain.
Pendekatan tersebut bertujuan mengembangkan budaya sekolah di mana persaingan terutama seharusnya dengan diri sendiri, bukan dengan teman sekelas.
Negara Skandinavia lain, yaitu Swedia, memegang teguh prinsip bahwa capaian akademis penting, tetapi manusia adalah yang utama. Pendidikan di negara ini menggabungkan literasi sosial-emosional (SEL) ke dalam standar nasional pendidikan dengan evaluasi pembelajaran mencakup student well-being dan dinamika sosial dalam kelas, bukan hanya capaian akademis.
Penelitian tahun 2024 di Swedia[14] menganalisis bagaimana pelatihan guru di Swedia secara sistemik melatih calon guru untuk membangun empati, kepekaan sosial, dan literasi emosi dalam praktik mengajar. Pelatihan ini menimbang bahwa empati bukan sekadar nilai moral, tetapi kompetensi profesional guru.
Penekanannya bukan hanya SEL umum, tetapi kompetensi interpersonal mencakup memahami perspektif, membangun kehangatan relasi, dan membaca emosi siswa yang semuanya merupakan inti empati.
Temuan ini penting karena menegaskan bahwa integrasi empati tidak cukup dihadirkan secara formal, tapi perlu dirumuskan secara jelas, diajarkan secara sistematis, dan dievaluasi secara terukur.
Saat konflik terjadi, anak tidak serta merta dihukum. Sebaliknya, mereka diajak berdialog untuk memulihkan hubungan. Proses ini melatih anak untuk melihat bahwa perilaku memiliki dampak emosional pada orang lain.
Bagaimana dengan Indonesia?

Empati merupakan kompetensi sosial yang berkembang melalui relasi, baik dengan guru yang hadir, keluarga yang suportif, dan lingkungan sekolah yang aman.
Jika Finlandia memiliki KiVa, Denmark memiliki Klassens tid, dan Swedia memasukkan SEL dalam standar pendidikannya, maka Indonesia perlu menemukan bentuknya sendiri berupa model empati yang relevan dengan konteks budaya, komunitas, dan tantangan keseharian.
Intinya, empati bukan mata pelajaran, melainkan ekosistem. Mengajarkan empati berarti membangun sekolah sebagai ruang kelekatan, ruang mendengar, dan ruang tumbuh emosional.
Penelitian tahun 2021[16] menemukan bahwa remaja dengan tingkat empati tinggi lebih cenderung mengambil posisi sebagai defender, yakni siswa yang berani menghentikan perundungan dan melindungi korban. Efek ini semakin kuat ketika relasi guru–siswa bersifat hangat dan suportif, karena hubungan tersebut memberi rasa aman dan meningkatkan sensitivitas moral[17] siswa terhadap penderitaan teman sebaya.
Keterlibatan emosional orang tua[18] juga merupakan faktor penting dalam mengembangkan empati afektif remaja. Ketika orang tua menyediakan ruang komunikasi yang terbuka dan responsif, anak lebih mampu mengatur emosi dan memahami perasaan orang lain. Sebaliknya, kurangnya kehadiran emosional orang tua berhubungan dengan meningkatnya kerentanan terhadap distress dan perilaku impulsif.
Tanpa pergeseran paradigma ini, sekolah akan terus gagal membaca tanda-tanda krisis psikologis siswa, kehilangan fungsi pelindungnya, dan hanya menjadi institusi yang menghasilkan capaian akademis tanpa nilai kemanusiaan.
Read more: Indonesia minim kebijakan publik berkualitas, bukti krisis empati di kalangan politisi[19]
References
- ^ Kasus ledakan bom di SMA 72 Jakarta (www.metrotvnews.com)
- ^ kematian tragis mahasiswa Universitas Udayana (www.bbc.com)
- ^ tidak memiliki tempat berkeluh kesah (news.detik.com)
- ^ meningkatkan risiko (www.who.int)
- ^ Bahaya ide bunuh diri pada remaja bila terlambat ditangani (theconversation.com)
- ^ UNICEF mencatat (www.unicef.org)
- ^ Cat Box/shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ riset tahun 2024 (ojspanel.undikma.ac.id)
- ^ Penelitian tahun 2024 di Cina (www.mdpi.com)
- ^ membaca situasi sosial (ojs.ual.es)
- ^ program KiVa (www.kivaprogram.net)
- ^ KiVa menekankan (www.kivaprogram.net)
- ^ klassens tid (waktu kelas) (www.edweek.org)
- ^ Penelitian tahun 2024 di Swedia (www.sciencedirect.com)
- ^ FiqihKE/shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ Penelitian tahun 2021 (ojs.ual.es)
- ^ rasa aman dan meningkatkan sensitivitas moral (ojs.ual.es)
- ^ Keterlibatan emosional orang tua (www.researchgate.net)
- ^ Indonesia minim kebijakan publik berkualitas, bukti krisis empati di kalangan politisi (theconversation.com)
Authors: Charyna Ayu Rizkyanti, Dosen Psikologi Perkembangan, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)